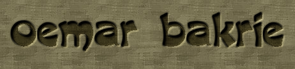o-bakrie.com -- Ujian nasional atau UN makin memprihatinkan. Tengok saja pelaksanaannya, selalu terjadi kebocoran soal. Padahal, Mendiknas selalu optimistis bahwa tidak akan ada kebocoran soal UN. Pelaksanaannya pada satu-dua tahun yang lalu memaksa pemerintah berpikir keras bagaimana cara mengantisipasi kebocoran soal.
KEMUDIAN muncul ide untuk membuat soal dalam 5 paket. Namun apa yang terjadi, tetap saja kebocoran soal terjadi di mana-mana. Jawaban dari soal yang akan diujikan telah beredar terlebih dahulu dengan jumlah sesuai dengan paketnya. Percaya atau tidak, ini adalah kejadian nyata di lapangan.
Rencananya, pemerintah bisa saja memberlakukan UN dengan 20 paket soal yang berbeda. Kehebatan pemerintah dalam mengantisipasi murninya nilai dari hasil UN sepertinya sudah dangkal. Banyak para pendidik merasa pesimistis dengan ide seperti ini.
Ada saja oknum yang lebih ’’cerdas’’ untuk menkonter upaya pemerintah dalam hal ini. Lalu, siapa yang dirugikan? Jelas, seluruh elemen bangsa ini rugi. Seorang guru yang sudah bekerja keras untuk mengasah kemampuan siswa ternyata usahanya kandas di tengah jalan.
Sepertinya, tidak ada bekas dari proses kegiatan belajar. Tiga tahun mengajar dan mendidik kalah hanya dengan kiriman SMS dan contekan jawaban. Miris, kerjanya terasa sia-sia, perangkat yang dibuat (bagi guru yang membuat perangkat) sepertinya tidak berfungsi untuk mencerdaskan anak bangsa. Untungnya, perangkat itu masih bisa bermanfaat bagi yang ’’bersertifikasi’’.
Pihak sekolah harusnya ikut merasa dirugikan, tentu bagi yang merasa! Mengapa? Jelas sekali dengan adanya kebocoran soal, maka usaha sekolah untuk mengadakan tambahan jam belajar menjadi sia-sia. Sekolah-sekolah sepertinya sudah tahu akan adanya kebocoran soal. Namun, mereka latah untuk tetap mengadakan tambahan jam belajar sebagai upaya serius menghadapi UN.
Namun apa yang terjadi, dengan adanya bocoran jawaban yang tersebar oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab akhirnya peserta didik 100 persen bisa lulus. Sia-sia, bukan? Masyarakat, sebagai pemilik peserta didik, harusnya juga merasa dirugikan. Bukan masalah lulus, tapi prosesnya.
Anak-anak yang masih kecil/remaja, pikirannya bersih, justru dididik untuk tidak jujur. Diajari menyontek dan bagaimana cara menyebarkan contekan dengan benar. Ini adalah krisis moral dari dampak UN yang sesungguhnya.
Di mana letak krisisnya? Anak-anak yang diajari tidak jujur akan tertanam dalam otak mereka, bahwa tidak jujur asal ramai-ramai tidak jadi masalah. Itu yang pertama. Kedua, negara ini sudah banyak koruptor. Pemerintah saat ini sedang berupaya memberantas mereka. Tidak mustahil pendidikan menyontek akan memupuk penyakit akut korupsi yang ada di negeri ini. Hasilnya krisis moral. Berani menyontek adalah modal utama untuk menjadi koruptor.
Pengawas ujian yang ditugaskan hanya bekerja sekadar sebagai fasilitator. Tugas mereka membacakan peraturan, membagi soal, dan lembar jawaban. Mereka akan salah manakala ketat dalam mengawas. Salah jika tidak membiarkan siswa menyontek. Akhirnya pura-pura tidak tahu. Akhirnya pun jadi benar-benar tidak tahu dan bodoh.
Masyarakat yang resah akibatnya akan menutup hati nurani mereka. Mereka takut anak-anaknya tidak lulus. Mereka tahu bahwa menyontek itu pekerjaan tidak baik (baca tidak halal). Tapi karena mereka takut anak-anaknya tidak lulus UN, akhirnya mengikuti pola yang salah ini.
Saya masih ingat sekali dengan berita tentang Ny. Siami. Dia mencoba jujur tentang pelaksanaan UN di SDN 2 Gadel pada tahun ajaran 2010/2011. Dengan kejujurannya, dia malah jadi terdakwa dan diusir dari desanya. Inilah masyarakat hasil dari pola/sistem pendidikan yang salah.
Sebenarnya, salah di mana? Mengutip pernyataan dari Sosiolog UI Imam Prasodjo, dia memaparkan bahwa kesalahan sistem pendidikan di negeri ini adalah pendidikan yang berorientasi pada hasil. Sementara proses tidak mengikutinya dengan baik. Nilai distandarkan secara nasional tanpa melihat sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing satuan pengelola pendidikan. Namun harus mencapai hasil yang sama. Acuannya, keberhasilan pendidikan adalah dengan berpatokan pada nilai UN.
Ini adalah salah satu tugas pemerintah dalam pemerataan proses pendidikan. Lalu apa bedanya anggaran pendidikan 2 persen dengan 20 persen? Ke mana larinya anggaran-anggaran tersebut?
Sangat jelas sekali perbedaannya, jika sekolah berstatus negeri harus disamakan dengan sekolah swasta yang siswanya tidak dipungut biaya pendidikan adalah hal yang konyol. Gurunya saja kadang harus menerima honor tiga bulan sekali. Jumlah honornya jika dibandingkan dengan gaji tukang cuci di rumahnya pun masih besar gaji tukang cucinya.
Buku pelajaran saja kadang tidak mampu mengadakan kok harus disamakan dengan sekolahan yang tiap hari siswanya bergaul dengan dunia internet. Sungguh ironis negeri ini.
Doktrin lulus 100 persen sudah mengakar, dari pusat hingga daerah dan masuk ke sekolah-sekolah. Akhirnya masyarakat yang jadi korban, mereka menjadi pesimis menghadapi sistem pendidikan yang seperti ini. Sebagian guru-guru dan kepala sekolah tertekan.
Mereka seolah-olah memikul beban yang berat terkait dengan kelulusan peserta didiknya. Satuan pendidikan yang memiliki raw matrial kurang bermutu harus mengimbangi sekolahan yang memiliki tingkat seleksi lebih ketat.
Finlandia pada 2003 menduduki peringkat pendidikan pertama dunia. Jika di Indonesia percaya bahwa ujian dan evaluasi bagi siswa merupakan bagian yang sangat penting bagi kualitas pendidikan, lain halnya dengan di negeri Nokia ini. Finlandia justru percaya bahwa ujian dan testing itulah yang menghancurkan tujuan belajar siswa.
’’Terlalu banyak testing membuat kita cenderung mengajarkan siswa, bagaimana cara untuk lolos ujian,’’ ungkap seorang guru di Finlandia. Padahal banyak aspek dalam pendidikan yang tidak bisa diukur dengan ujian. Baru pada usia 18 tahun, siswa mengambil ujian untuk mengetahui kualifikasi mereka di perguruan tinggi dan dua per tiga lulusan berhasil melanjutkan ke perguruan tinggi.
Peringkat pendidikan Indonesia yang meraih peringkat ke-69 sepertinya tidak terlalu berpengaruh terhadap perbaikan pendidikan di Indonesia jika orientasinya tidak diubah. Beberapa guru sangat mendukung sistem pendidikan dengan evaluasi akhir menggunakan Ebta/Ebtanas. Biarkan satuan pendidikan menggunakan otoritas mereka dalam meluluskan siswanya.
Kemudian untuk jenjang pendidikan selanjutnya harus menggunakan seleksi tes. Sehingga dengan tes tersebut akan diketahui kemampuan masing-masing calon peserta didik. Ini tentu lebih adil, masyarakat lebih tenang, guru-guru bisa lebih kreatif, inovatif, dan introspektif.
Sanggupkah bangsa ini mengamalkan kejujuran dalam pendidikan? Jangan kemudian jika ada yang mencoba jujur malah diasingkan dan dihujat seperti Ny. Siami. (*)
Continue reading →
KEMUDIAN muncul ide untuk membuat soal dalam 5 paket. Namun apa yang terjadi, tetap saja kebocoran soal terjadi di mana-mana. Jawaban dari soal yang akan diujikan telah beredar terlebih dahulu dengan jumlah sesuai dengan paketnya. Percaya atau tidak, ini adalah kejadian nyata di lapangan.
Rencananya, pemerintah bisa saja memberlakukan UN dengan 20 paket soal yang berbeda. Kehebatan pemerintah dalam mengantisipasi murninya nilai dari hasil UN sepertinya sudah dangkal. Banyak para pendidik merasa pesimistis dengan ide seperti ini.
Ada saja oknum yang lebih ’’cerdas’’ untuk menkonter upaya pemerintah dalam hal ini. Lalu, siapa yang dirugikan? Jelas, seluruh elemen bangsa ini rugi. Seorang guru yang sudah bekerja keras untuk mengasah kemampuan siswa ternyata usahanya kandas di tengah jalan.
Sepertinya, tidak ada bekas dari proses kegiatan belajar. Tiga tahun mengajar dan mendidik kalah hanya dengan kiriman SMS dan contekan jawaban. Miris, kerjanya terasa sia-sia, perangkat yang dibuat (bagi guru yang membuat perangkat) sepertinya tidak berfungsi untuk mencerdaskan anak bangsa. Untungnya, perangkat itu masih bisa bermanfaat bagi yang ’’bersertifikasi’’.
Pihak sekolah harusnya ikut merasa dirugikan, tentu bagi yang merasa! Mengapa? Jelas sekali dengan adanya kebocoran soal, maka usaha sekolah untuk mengadakan tambahan jam belajar menjadi sia-sia. Sekolah-sekolah sepertinya sudah tahu akan adanya kebocoran soal. Namun, mereka latah untuk tetap mengadakan tambahan jam belajar sebagai upaya serius menghadapi UN.
Namun apa yang terjadi, dengan adanya bocoran jawaban yang tersebar oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab akhirnya peserta didik 100 persen bisa lulus. Sia-sia, bukan? Masyarakat, sebagai pemilik peserta didik, harusnya juga merasa dirugikan. Bukan masalah lulus, tapi prosesnya.
Anak-anak yang masih kecil/remaja, pikirannya bersih, justru dididik untuk tidak jujur. Diajari menyontek dan bagaimana cara menyebarkan contekan dengan benar. Ini adalah krisis moral dari dampak UN yang sesungguhnya.
Di mana letak krisisnya? Anak-anak yang diajari tidak jujur akan tertanam dalam otak mereka, bahwa tidak jujur asal ramai-ramai tidak jadi masalah. Itu yang pertama. Kedua, negara ini sudah banyak koruptor. Pemerintah saat ini sedang berupaya memberantas mereka. Tidak mustahil pendidikan menyontek akan memupuk penyakit akut korupsi yang ada di negeri ini. Hasilnya krisis moral. Berani menyontek adalah modal utama untuk menjadi koruptor.
Pengawas ujian yang ditugaskan hanya bekerja sekadar sebagai fasilitator. Tugas mereka membacakan peraturan, membagi soal, dan lembar jawaban. Mereka akan salah manakala ketat dalam mengawas. Salah jika tidak membiarkan siswa menyontek. Akhirnya pura-pura tidak tahu. Akhirnya pun jadi benar-benar tidak tahu dan bodoh.
Masyarakat yang resah akibatnya akan menutup hati nurani mereka. Mereka takut anak-anaknya tidak lulus. Mereka tahu bahwa menyontek itu pekerjaan tidak baik (baca tidak halal). Tapi karena mereka takut anak-anaknya tidak lulus UN, akhirnya mengikuti pola yang salah ini.
Saya masih ingat sekali dengan berita tentang Ny. Siami. Dia mencoba jujur tentang pelaksanaan UN di SDN 2 Gadel pada tahun ajaran 2010/2011. Dengan kejujurannya, dia malah jadi terdakwa dan diusir dari desanya. Inilah masyarakat hasil dari pola/sistem pendidikan yang salah.
Sebenarnya, salah di mana? Mengutip pernyataan dari Sosiolog UI Imam Prasodjo, dia memaparkan bahwa kesalahan sistem pendidikan di negeri ini adalah pendidikan yang berorientasi pada hasil. Sementara proses tidak mengikutinya dengan baik. Nilai distandarkan secara nasional tanpa melihat sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing satuan pengelola pendidikan. Namun harus mencapai hasil yang sama. Acuannya, keberhasilan pendidikan adalah dengan berpatokan pada nilai UN.
Ini adalah salah satu tugas pemerintah dalam pemerataan proses pendidikan. Lalu apa bedanya anggaran pendidikan 2 persen dengan 20 persen? Ke mana larinya anggaran-anggaran tersebut?
Sangat jelas sekali perbedaannya, jika sekolah berstatus negeri harus disamakan dengan sekolah swasta yang siswanya tidak dipungut biaya pendidikan adalah hal yang konyol. Gurunya saja kadang harus menerima honor tiga bulan sekali. Jumlah honornya jika dibandingkan dengan gaji tukang cuci di rumahnya pun masih besar gaji tukang cucinya.
Buku pelajaran saja kadang tidak mampu mengadakan kok harus disamakan dengan sekolahan yang tiap hari siswanya bergaul dengan dunia internet. Sungguh ironis negeri ini.
Doktrin lulus 100 persen sudah mengakar, dari pusat hingga daerah dan masuk ke sekolah-sekolah. Akhirnya masyarakat yang jadi korban, mereka menjadi pesimis menghadapi sistem pendidikan yang seperti ini. Sebagian guru-guru dan kepala sekolah tertekan.
Mereka seolah-olah memikul beban yang berat terkait dengan kelulusan peserta didiknya. Satuan pendidikan yang memiliki raw matrial kurang bermutu harus mengimbangi sekolahan yang memiliki tingkat seleksi lebih ketat.
Finlandia pada 2003 menduduki peringkat pendidikan pertama dunia. Jika di Indonesia percaya bahwa ujian dan evaluasi bagi siswa merupakan bagian yang sangat penting bagi kualitas pendidikan, lain halnya dengan di negeri Nokia ini. Finlandia justru percaya bahwa ujian dan testing itulah yang menghancurkan tujuan belajar siswa.
’’Terlalu banyak testing membuat kita cenderung mengajarkan siswa, bagaimana cara untuk lolos ujian,’’ ungkap seorang guru di Finlandia. Padahal banyak aspek dalam pendidikan yang tidak bisa diukur dengan ujian. Baru pada usia 18 tahun, siswa mengambil ujian untuk mengetahui kualifikasi mereka di perguruan tinggi dan dua per tiga lulusan berhasil melanjutkan ke perguruan tinggi.
Peringkat pendidikan Indonesia yang meraih peringkat ke-69 sepertinya tidak terlalu berpengaruh terhadap perbaikan pendidikan di Indonesia jika orientasinya tidak diubah. Beberapa guru sangat mendukung sistem pendidikan dengan evaluasi akhir menggunakan Ebta/Ebtanas. Biarkan satuan pendidikan menggunakan otoritas mereka dalam meluluskan siswanya.
Kemudian untuk jenjang pendidikan selanjutnya harus menggunakan seleksi tes. Sehingga dengan tes tersebut akan diketahui kemampuan masing-masing calon peserta didik. Ini tentu lebih adil, masyarakat lebih tenang, guru-guru bisa lebih kreatif, inovatif, dan introspektif.
Sanggupkah bangsa ini mengamalkan kejujuran dalam pendidikan? Jangan kemudian jika ada yang mencoba jujur malah diasingkan dan dihujat seperti Ny. Siami. (*)
sumber : Radar Lampung